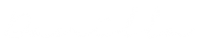Saya punya sifat buruk susah memuji, bahkan ketika sudah menenggak setengah dari sebotol penuh Jaggermeister pemberian Danilla. Saya tidak pernah suka Jaggermeister, aroma herbalnya selalu meninggalkan kesan antiseptik yang gampang memancing asam lambung naik, mual-mual terintimidasi muntah sendiri. Tekanan seperti itu biasanya keluar setelah 5 sloki pertama kelar dan melepas sendawa. Seketika itu juga bau kencing rusa akan menguasai peredaran, dan dalam kondisi orbit miring begini saya ogah, tidak – alias belum berani menghakimi secara terbuka apakah Fingers adalah sebuah karya yang buruk, atau lebih halusnya, sebuah karya yang biasa-biasa saja.
Tapi mata kemudian tersedot menghayati cahaya 1 watt yang mengumbar temaram dari tepi meja. Pendar-pendarnya menjuntai, memberikan magnet kepada butiran-butiran debu yang melayang-layang membentuk satu trik ilusi memahami sepi. Beberapa orang suka menebar cuka di atas luka, beberapa lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan bermain cinta; dalamnya hati perempuan siapa yang duga?
Saya mengagumi perempuan karena segala keluh kesah mereka yang seperti tiada ada habisnya, itu membuat mereka merepotkan sekaligus menawan, sementara para lelaki – kami – terlalu sibuk menuntut diri hingga tidak tahu caranya agar bisa mengerti. Dalam sebuah wawancara gang bang dengan Danilla saya pernah menanyakan sesuatu tentang bunuh diri kepadanya. Saya pribadi menyetujui tindakan bunuh diri dan penasaran Danilla pun sama setelah mendengarkan betapa murungnya album Lintasan Waktu memilih jalan di persimpangan.
Bunuh diri adalah luapan kebebasan bagi jiwa-jiwa yang gusar. Cara itu memperlihatkan batas-batas keanggunan, keberanian mutlak dan kasih sayang metaforik seorang manusia, sampai sejauh mana kita mampu menghormati diri kita sendiri, sepenuhnya bertanggung jawab secara mandiri dan melancarkan veto. Oleh sebab itu saya tidak bisa menganggap sebuah penghargaan terhadap diri sendiri ‘telah pantas’ dilakukan sebelum seorang manusia dapat berhenti mengharapkan perjudian nasibnya berakhir di tangan hati dan pikiran pihak lain.
Sewaktu Danilla menyatakan dirinya tak mendukung tindakan bunuh diri, saya tidak kecewa, tapi lantas terpikat ketika dia melanjutkan kalimatnya dengan
menceritakan percobaannya minum air parfum dalam aksi impromptu mengakhiri hidup pada usia bocah. Saya tidak terkejut, tentu saja, mengetahui adanya tendensi tersebut malah membuat saya sedikit lebih mengerti – kalau tidak bisa dibilang lega – darimana semua mellon collie and the infinite sadness itu berasal.
Satu kesalahan cukup besar kala mengomentari fenomena kesenduan massal bernama Danilla selama dua tahun terakhir ini adalah dengan menyebutnya penyanyi penjual kesedihan, seperti dipantulkannya kembali langsung kepada saya. “Menurut elo,” kata dia, “menjual atau berbagi kesedihan?” Hee-haw. Itu jawaban yang bagus. Karena bicara kesedihan berarti juga bicara kemampuan, seberapa dalam kita mampu menghanyutkan diri dan tetap tegar mengarungi perjalanan. Berusaha tidak terkurung dengan membaca tanda-tandanya, membenam otak hingga sejengkal bahu ke dagu, terbuai dan melamun . . .
. . . Tampaknya hampir semua penyanyi perempuan paling keren yang pernah hidup di sini adalah orang-orang yang sedih. Hope Sandoval. Amy Winehouse. Billie Holiday. Janis Joplin. Kartika Jahja. Frau. Fiona Apple. Nico. Mereka bernyanyi seperti Cupid depresif, suara horny dari hadapan cermin yang, baik secara gegabah maupun matang, selalu berhasil menggoda naluri psikis manusia berkobar deras. Untuk kemudian menghadiahi dirinya sendiri sebuah ‘penghargaan diri’. Orang-orang sedih adalah orang-orang yang berjalan dengan kebanggaan, sesungguhnya. Rasanya akan meremang di sekujur hidung sesaat kau mampu menerbitkan senyum di antara nafas yang tersengal, mendengarkan lagu-lagu nina bobo yang diputar pada pukul setengah empat pagi menolak tidur.
Pilih: jurang atau tepian?
Atau jika itu terlalu gelap, geser kata ‘sedih’ dengan ‘romantik’: ‘(hampir) semua penyanyi perempuan paling keren yang pernah hidup di planet ini adalah orang-orang yang romantik.’ Yes, satu buket kesedihan buat kalian semua, silakan diambil, terserah, lompat ke jurang atau cuma melamun di tepian. Buat saya, setelah tiga kali membiarkan Fingers terputar beruntun, kata ‘romantik’ ternyata lebih tepat diganti dengan ‘dingin’. Itu membuat kelima lagunya punya kesan menjalar, menusuk di sudut pikiran yang berdebar. Seakan Danilla sendirilah yang tiba-tiba mengembuskannya : ‘(hampir semua penyanyi) perempuan paling sedih yang pernah hidup di planet romantik ini adalah orang-orang yang dingin.’
Dia mengerjakan album itu sendirian. Lafa Pratomo cuma diajak memainkan isian kecil di lagu jari tengah, “Middle”. Saya pun coba menerka-nerka apa motivasi di balik individualitas pembuatan Fingers, mungkin sesederhana terpantik ‘ide giting’, atau malah sebetulnya merupakan buah dari hal yang lebih serius, Danilla tengah meragukan kemampuannya menulis musik dan terpicu ego ‘sebagus apa jari jemarinya mencipta bila dilepas sendiri’. Tidak ada bantuan, hanya petik gitar, tuts organ & hati seekor kucing yang murung. Moody kumat. Satu kata yang terbayang sekarang adalah, entah kenapa, tirai. Pasti karena terlalu lama menatap foto di sampulnya.
Jika album ini ternyata benar tentang ego, semestinya Danilla tidak perlu mencemaskan melodi-melodi yang diciptakannya sendiri, dia punya selera kelam yang valid untuk urusan lagu-lagu nanar menginspirasi; melainkan kemampuan menulis lirik Bahasa Inggris-nya yang frigid. Saya tidak peduli dengan grammar, tapi menyarankannya tetap menulis dalam Indonesia saja kalau cuma bisa menghasilkan kalimat-kalimat permukaan yang tak menggerakkan apa-apa. Saya menyadari kalimat-kalimat permukaan itu cukup lumayan tercecer di beberapa lagu, meskipun tidak sampai mengganggu khidmat album secara keseluruhan.
‘Is this worth fighting for?
-“Index”
Is this worth losing more of our kind?
Will it last?
Will it take us somewhere, somewhere to love?’
Mencoba politis sekadar basa-basi. Pertanyaan-pertanyaan masa bodoh jika tidak ada yang menjawabnya. Mungkin Danilla sedang geram menonton Instagram dan mengekspresikan kekesalannya terhadap media-media setiran. Taruhlah, andaikan sampulnya tidak menyertakan detail lirik di dalamnya, mungkin paragraf ini tidak akan pernah tertulis. Saya pasti luput menyadarinya, duluan terlena untaian “Pinky”, si jari kelingking yang rapuh.
Kelihatanya cuma itu satu-satunya respons negatif saya terkait Fingers, selebihnya tidak ada masalah berarti, less jazzy. Toh, ini cuma album singkat. Tidak ada yang spesial selain lagu-lagu pop merana yang enak dipakai konstan menyendiri. Saya menikmatinya selagi sensitif. Mari kita angkatkan sulang kepadanya . . . kepada perilaku hewani dan praktik khayal babu, kepada idealisme dan buku-buku gratis, kepada keheningan, kepada abu kretek dan air kencing Rusa, kepada Beth Gibbons, kepada setiap tubuh hangat dan seks tanpa kondom . . . dan kepada ‘kehidupan yang setimpal’, kapan dan di mana pun saya mencuri kutipan dari seorang penulis.
Res Ipsa Loquitur.